KESADARAN SEJARAH
Tanpa mengetahui sejarahnya, suatu bangsa tidak mungkin mengenal dan memiliki identitasnya(Sartono, 1992). Realitas kekinian
Lebih dari setengah abad
Sebagian besar generasi yang hidup di awal milenium ketiga ini harus memikul beban yang teramat berat karena keteledoran bangsa ini membaca sejarah. Kesadaran bangsa ini baru terusik manakala kebanggaan “persatuan dan kesatuan” yang selama ini digembar-gemborkan ternyata hanya sebuah mitos yang berakar pada pembodohan anak bangsa. Maka ketika akselerasi dinamika sosial politik semakin diwarnai tuntutan-tuntutan yang mencengangkan serta maraknya konflik horizontal, maka kita gagap menyikapinya.
Kebanggaan nusantara sebagai untaian zamrut yang menjadi kidung merdu selama ini terancam putus. Maka seperti prediksi
Berbagai macam gejolak sosial senantiasa diwarnai penonjolan simbol-simbol perbedaan suku, ras, agama dan antar golongan. Apa yang muncul saat ini seolah merupakan akumulasi kerapuhan dari kenyataan-kenyataan yang selama ini dibungkus dalam wadah bhineka tunggal ika yang meninggalkan prinsip-prinsip keadilan.
Dalam konteks realitas empiris yang demikian itu lalu apa yang mampu diperbuat (sebagai bangsa) selain berefleksi, retrospeksi, meluruskan kembali jalan sejarah. Momentum ini seharusnya menyadarkan bahwa selama ini kita dipaksa untuk memberhalakan persatuan dan kesatuan, sedangkan praktek ketidak adilan berlangsung dalam kewajaran dan tanpa kontrol bahkan menjadi bagian yang menemukan justifikasinya.
QUO VADIS NASIONALISME
Bangsa bukanlah asosiasi sukarela, melainkan komunitas dimana sebagian besar anggotanya dilahirkan dan mati sehingga kita bersama-sama terikat dengan saudara sebangsa dalam sebuah komunitas takdir. Selain itu komunitas ini memiliki sejarah yang paling panjang , sehingga kewajiban-kewajiban kita tidak hanya bagi mereka yang sezaman tetapi juga bagi para anggota komunitas dimasa lalu dan masa depan, kita harus berpegang teguh pada prinsip kebangsaan, sementara berjuang untuk menempa identitas nasional yang dapat mengakomodasi pluralisme (Miller, 1995; 416-420). Prinsip kebangsaan tersebut adalah kesatuan (unity), kebebasan (liberty), kesamaan (equality), kepribadian (personality) dan prestasi (performance) (Sartono, 1995;15)
Paralel dengan tesis di atas, maka nasionalisme kita lahir dan berkembang sebenarnya bukan saja sekedar akibat penjajahan. Nasionalisme kita adalah hasil dari kekuatan imajinasi dan keresahan intelektual, yang mengharuskan mereka, para pelopor bangsa, melihat jauh, melampaui ikatan komunitas riil masing-masing. Dalam konteks tersebut faktor ras, etnisitas, bahasa, dan agama dilihat bukan sebagai hal yang harus menghalangi konsepsi awal mereka tentang nasionalisme. Maka saat ini kita seharusnya menghargai pengalaman kolektif (sejarah) tersebut sebagai basis untuk tetap menyatakan diri sebagai bangsa
Apabila pengalaman sejarah bangsa ini, yang di dalamnya melekat pelajaran tentang nilai-nilai dan semangat pengorbanan dalam arti menempatkan kepentingan sendiri di belakang kepentingan bangsa tidak bisa merekatkan kembali zamrut yang akan terlepas serta mengembalikan kesadaran berbagai kelompok yang merasa paling berhak atas hitam putihnya negeri ini, lalu bagaimana kita harus memaknai proses historis tersebut? Seharusnya kita mau menoleh kebelakang, ke suatu wilayah zaman dimana bangsa ini mengukir pengalaman kolektif, berjuang menumbuhkan nasionalisme dalam gelombang pertentangan yang teramat keras, namun ternyata mampu dilampaui. Kini ketika identitas nasional telah diwujudkan semestinya kita mampu memaknai dan mempertahankanya.
Apabila kita kembali pada bangsa sebagai komunitas takdir sebagaimana disebutkan dalam tesis Muller di atas, seharusnya nasionalisme dimaknai sebagai suatu yang given, tetapi melihat realitas Indonesia yang mengisyaratkan goyahnya pondasi kebangsaan akhir-akhir ini, tampaknya kenyataan tersebut lebih menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia tidak lebih dari suatu imagined communities, gambaran tentang bangsa seperti dikemukakan oleh Anderson. Komunitas bangsa
KESADARAN SEJARAH
Suatu bangsa terbentuk dari pengalaman bersama di masa lampau, maka sejarah menjadi esensial bagi nasion, oleh karena itu pengetahuan sejarah menjadi dasar pendidikan nasional. Dalam hal ini kita ternyata masih harus mengakui urgensi pengajaran sejarah, karena tujuan pengajaran sejarah yang pokok adalah;
1. Supaya manusia mengenal dirinya sendiri sebagai kelompok, misalnya bangsa
2. Menjadikan titik tolak pembangunan masa kini dan masa datang, karena peristiwa sejarah berkesinambungan dari lampau, kini dan datang.
3. Menemukan ilham dan keteladanan dari masa lampau demi hidup pada masa sekarang dan yang akan datang.
4. Memperkenalkan kepada peserta didik bahwa dunia itu berproses dan berubah
5. Membangkitkan apresiasi kultural serta persahabatan antar bangsa menuju perdamaian dunia.
Konflik sosial yang mengemuka saat ini seharusnya dapat direduksi apabila bangsa ini sedikit saja memiliki kesadaran sejarah, karena dari kesadaran tersebut berarti kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kolektif sebagai bangsa. Ekskalasi konflik pada level elite maupun horizontal yang semakin luas pada saat ini merupakan refleksi belum sempurnanya penerapan prinsip nasionalisme, kesatuan nasional kita ternyata masih rapuh. Hal tersebut mengindikasikan lemahnya kesadaran kolektif (collective consciousness) bangsa ini, yang berarti lemahnya kesadaran sejarah.
Dengan melihat kenyataan
Kesadaran nasional berakar pada kesadaran sejarah. Kesadaran tersebut dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi kebanggaan nasional dan memperkuat kebanggaan
Dengan menoleh kebelakang, menengok pengalaman sejarah bangsa
1. Perkembangan ekonomis yang menciptakan konflik kelas berdasarkan perbedaan keberhasilan dalam kemajuan pembangunan ekonomi
2. Birokrasi yang ambivalen, dengan tidak adanya pemisahan urusan/kepentingan formal kedinasan dan yang pribadi, dengan dampak
3. Kecenderungan sektarian
4. Kepemimpinan di tingkat bawah berkurang kewibawaannya serta cenderung lebih melayani atasan
5. Mentalitas materialis lebih menentukan hubungan sosial, semakin bersifat egosentrisme, serta mengalami dehumanisasi.
6. Baik di bidang pemerintahan maupun swasta, primordialisme semakin dominan (Sartono, 1999; 48-49) .
Orientasi baru yang urgen dipahami dan diaktualisasikan oleh seluruh komponen bangsa ini;
1. Digantikannya cara berfikir ekonomisme oleh cara berfikir yang mendasarkan pada keadilan sosial.
2. Digantikannya individualisme oleh cita-cita kemasyarakatan
3. Orientasi elitis digantikan oleh orientasi
4. Budaya mitis digantikan budaya ilmiah
5. Kesadaran teknokratis digantikan oleh kesadaran “hati nurani”.
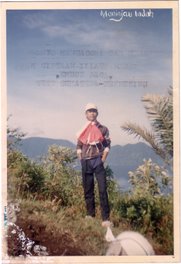
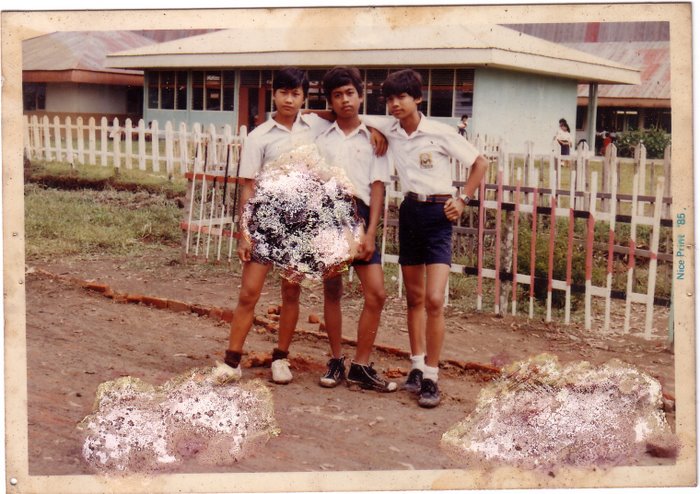
No comments:
Post a Comment